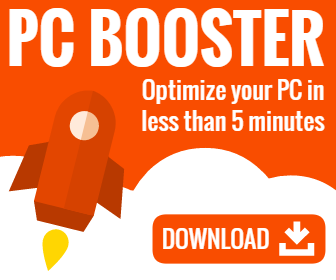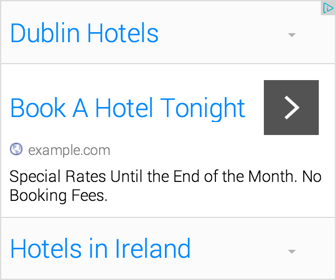Oleh : Rafasya Ghani )*
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat menanggapi gelombang tekanan ekonomi global yang ditimbulkan oleh kebijakan proteksionisme Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Dalam menghadapi perang tarif yang dikenakan sebesar 32% terhadap produk ekspor asal Indonesia, pemerintah mengedepankan strategi diplomasi adaptif sebagai bentuk respons yang terukur dan strategis.
Delegasi tingkat tinggi dari Indonesia telah diberangkatkan menuju Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan jajaran pejabat utama pemerintah AS. Selama periode tenggat penundaan pengenaan tarif oleh Trump hingga 9 Juni 2025, pemerintah memanfaatkan waktu secara maksimal untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional melalui jalur diplomatik.
Tim negosiator terdiri dari enam tokoh utama yang merepresentasikan kekuatan diplomatik dan ekonomi Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Ketua Dewan Energi Nasional Mari Elka Pangestu, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, serta Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, menjadi garda depan dalam merumuskan kesepakatan yang mampu meredam dampak buruk dari kebijakan tarif Trump.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa Indonesia menjadi negara pertama yang diundang ke Washington sebagai mitra dialog strategis. Langkah ini menunjukkan pengakuan atas posisi Indonesia sebagai kekuatan menengah (middle power) yang memiliki kapasitas diplomatik cukup kuat di tengah tekanan ekonomi global.
Negosiasi dilakukan secara intensif dengan U.S. Trade Representative, Secretary of Treasury, dan Secretary of Commerce. Fokus utama dalam upaya negosiasi tersebut yakni mencakup proposal non-paper terkait relaksasi tarif dan hambatan non-tarif, kerja sama investasi, sektor keuangan, serta penyusunan kerangka perdagangan bilateral yang lebih inklusif dan seimbang.
Salah satu isu krusial yang disoroti ialah kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Pemerintah menyepakati relaksasi terbatas hanya untuk sektor teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang berasal dari Amerika Serikat.
Menurut Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, keputusan ini bersifat selektif dan tidak akan mengganggu eksistensi perusahaan dari negara lain yang telah taat aturan TKDN sebesar 35%.
Di sisi fiskal, pemerintah menawarkan relaksasi berupa penurunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor dan Pajak Penghasilan (PPh) Impor untuk produk asal AS. Tarif PPh 22 impor untuk barang dengan API dipangkas dari yang sebelumnya 2,5% kini menjadi 0,5%, khusus untuk produk elektronik, seluler, dan laptop. Sedangkan bea masuk yang semula 5-10% disesuaikan menjadi 0-5%.
Langkah berikutnya berupa peningkatan investasi bilateral. Pemerintah mendorong BUMN seperti Pertamina dan perusahaan teknologi untuk semakin memperluas investasi di Amerika Serikat. Strategi ini menjadi bagian dari kompromi yang dirancang agar perusahaan-perusahaan AS juga memperbesar porsi investasinya di Indonesia.
Selain itu, pemerintah menyampaikan komitmen untuk meningkatkan volume impor dari AS senilai US$18-19 miliar sebagai upaya untuk menyeimbangkan neraca perdagangan. Komoditas yang direncanakan meliputi produk agrikultur seperti gandum dan kedelai, peralatan teknik, serta energi seperti LPG dan LNG.
Sementara itu, pengamat intelijen dan keamanan nasional, Dr. Stepi Anriani, menilai bahwa perang tarif akibat adanya kebijakan proteksionisme Presiden Amerika Serikat Donald Trump memicu ancaman fragmentasi ekonomi global yang lebih dalam.
Fragmentasi tersebut berpotensi untuk mengubah struktur rantai pasok internasional dan semakin mempercepat terbentuknya blok-blok ekonomi baru. Dalam kondisi ini, Indonesia sebenarnya dihadapkan pada tiga opsi, antara lain: melawan hegemoni AS, tunduk pada skenario dominasi AS, atau memainkan peran sebagai penengah yang netral namun strategis.
Dr. Stepi menggarisbawahi pentingnya memperkuat struktur ekonomi domestik sebagai tameng utama. Menurutnya, stabilitas harga dan daya beli masyarakat menjadi fondasi yang sama sekali tidak boleh tergantikan dalam menghadapi tekanan eksternal. Upaya menarik investasi, memperluas kemitraan multilateral, dan meningkatkan kapasitas intelijen ekonomi menjadi agenda prioritas untuk meningkatkan ketahanan nasional.
Posisi geografis Indonesia di jantung Indo-Pasifik membuat negara ini tidak bisa hanya menjadi penonton saja dalam dinamika global yang kian memanas. Ketegangan di Laut Tiongkok Selatan, konflik di Timur Tengah, serta perseteruan AS-Tiongkok, memerlukan ketangguhan diplomasi Indonesia yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dan visioner.
Diplomasi adaptif yang dijalankan pemerintah bukan hanya sekadar untuk merespons kebijakan sepihak dari AS, tetapi juga sekaligus menandai adanya transformasi peran Indonesia di kancah global.
Sebagai negara dengan posisi strategis dan sejatinya memiliki kekuatan ekonomi menengah, Indonesia juga dapat memimpin inisiatif baru seperti Global South Economic Dialogue Initiative untuk membentuk platform konsultatif bagi negara-negara berkembang lain dalam upaya untuk menghadapi dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian seperti sekarang ini.
Dengan seluruh strategi tersebut, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden RI kedelapan, Prabowo Subianto terus berupaya untuk menjadikan Tanah Air bukan hanya sebagai negara yang mampu bertahan di tengah badai global, melainkan juga sekaligus sebagai bangsa berkekuatan yang mampu membentuk arus.
Dalam menghadapi Perang Tarif akibat kebijakan proteksionisme Donald Trump, diplomasi adaptif bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak yang akan menentukan posisi Indonesia dalam percaturan ekonomi internasional ke depan. (*)
)* Penulis adalah pengamat ekonomi